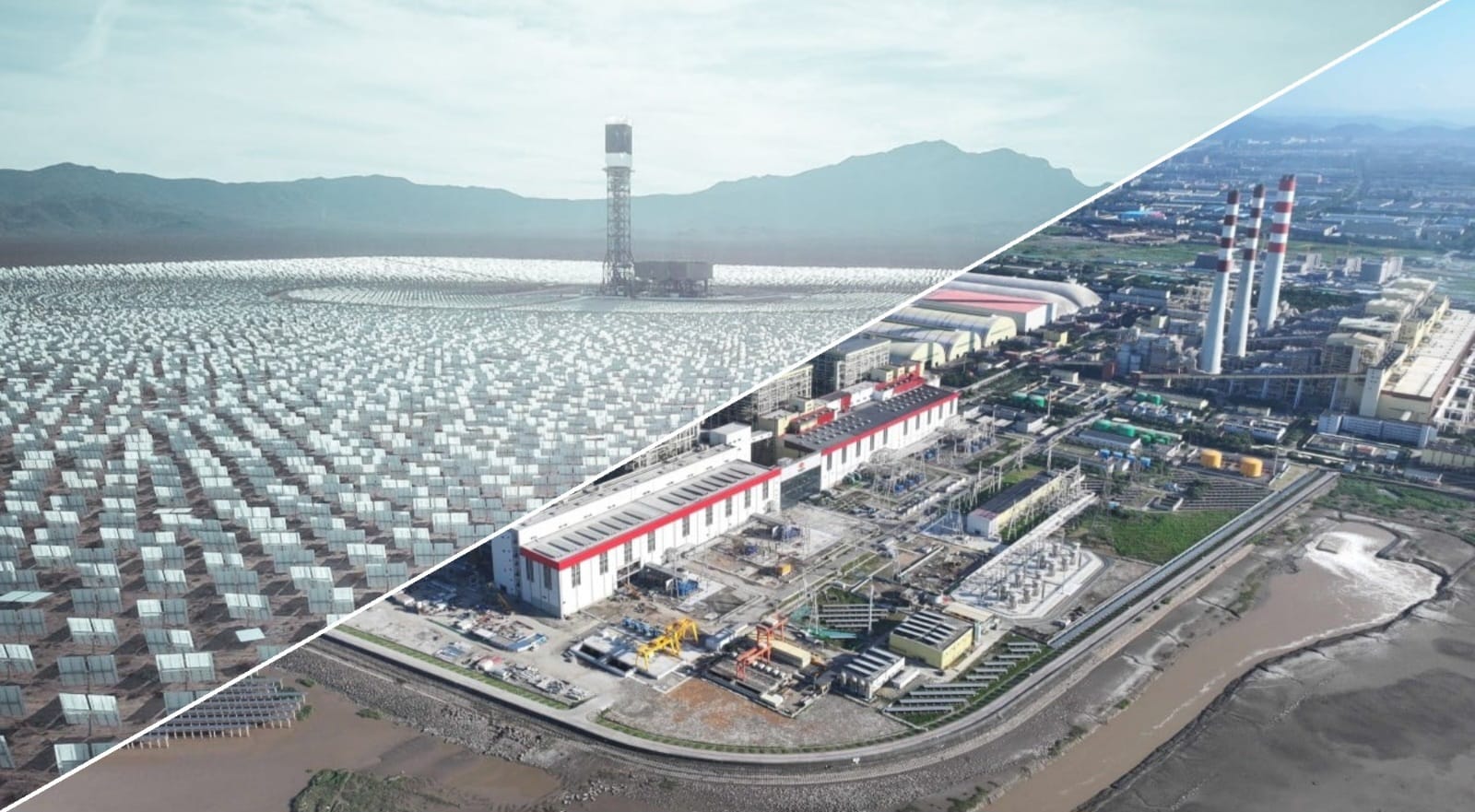AMBISI pemerintah membangun proyek waste-to-energy (WtE) kini memasuki babak baru. Proyek yang digadang sebagai jawaban atas krisis sampah perkotaan itu direncanakan hadir di 33 provinsi. Namun, di balik optimisme, tersimpan pekerjaan rumah lama. Proyek serupa sebelumnya banyak tersendat dan belum menunjukkan hasil nyata.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memastikan pembiayaan proyek WtE akan bersumber dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Klaim ini sekaligus membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menyebut APBN akan menanggung sebagian.
Pemerintah juga tengah menyiapkan revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan tipping fee, biaya yang biasanya dibayarkan pemerintah daerah kepada pengelola sampah. Sebagai gantinya, daerah diwajibkan menyediakan lahan dan menjamin pasokan sampah minimal 20 tahun.
Baca juga: PLTSa di 12 Kota Masih Mandek, Evaluasi Jadi Kunci Percepatan
Namun, sejumlah kalangan khawatir skema ini justru berisiko. Jika pasokan dan tata kelola sampah tidak konsisten, proyek bisa menjadi beban keuangan baru, baik bagi negara maupun PLN sebagai pembeli listrik.
Realitas Sampah Perkotaan
Timbunan sampah Indonesia mencapai 33,8 juta ton per tahun. Hanya sekitar 60% yang terkelola, sisanya 40% masih berakhir mencemari lingkungan. Kota-kota besar menjadi episentrum masalah, sementara infrastruktur pengolahan masih terbatas.
Baca juga: Krisis Sampah 2028, Indonesia di Ambang Darurat Lingkungan
Pemerintah berupaya mentransformasi 343 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill. Di samping itu, dibidik pembangunan 250 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan 42.000 TPS3R berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Total investasi yang disiapkan untuk transformasi ini mencapai Rp300 triliun.

Sorotan Akademisi dan Praktisi
Pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran, menilai proyek WtE rawan gagal bila tata kelola tidak diperbaiki. “Sampah adalah produk akhir. Jika seluruh beban, dari hulu hingga hilir, dibebankan ke pengembang, itu costly dan ekonomis tidak mungkin,” ujarnya.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menambahkan, karakter sampah Indonesia yang 70% organik dan berkadar air tinggi membuat PLTSa butuh pre-treatment. Proses tambahan ini menambah biaya investasi dan risiko finansial.
Baca juga: 30 Kota Siap Ubah Sampah Jadi Energi, 2029 Jadi Target
Direktur Celios, Bhima Yudhistira, juga mengingatkan bahwa biaya pembangunan PLTSa lebih mahal dibandingkan energi terbarukan lain seperti PLTS atap atau mikrohidro. “Yang mahal justru pemilahan sampah. Tanpa itu, PLTSa berisiko menghadapi limbah berbahaya,” katanya.
Antara Lompatan Besar dan Risiko Gagal
Pemerintah menargetkan 100% pengendalian sampah nasional pada 2029. Namun, waktu yang tersisa tinggal kurang dari lima tahun, sementara pembangunan satu unit PLTSa membutuhkan 3–4 tahun. Tanpa pengerjaan serentak di banyak lokasi, target itu sulit tercapai.
Baca juga: Jakarta Bangun PLTSA untuk Energi Bersih dan Dana Infrastruktur
Di sisi lain, masih ada tarik-menarik kewenangan antara Danantara, PLN, dan Kementerian ESDM. Sampai kini, penugasan resmi kepada PLN belum diputuskan. Pemerintah masih menunggu verifikasi investor oleh Danantara.
Proyek ini bisa menjadi lompatan besar bila tata kelola jelas, teknologi tepat, dan pembiayaan terukur. Sebaliknya, tanpa fondasi kuat, PLTSa hanya akan menambah daftar proyek ambisius yang gagal menjawab krisis sampah dan energi. ***